Opini
Big Data dan Etika: Mengapa Kita Harus Kritis dalam Era Datafikasi
Pernahkah Anda bertanya ke mana perginya data pribadi Anda setelah mengakses aplikasi kesehatan?
TRIBUNJATIMTIMUR.COM - Di era digital saat ini, kehidupan manusia secara perlahan namun pasti tengah “ditransformasikan menjadi data.” Mulai dari jejak pencarian di Google, unggahan di Instagram, hingga rekam jejak kesehatan melalui aplikasi kebugaran, semuanya menghasilkan data. Proses ini dikenal dengan istilah datafikasi, yaitu perubahan aktivitas sosial dan kehidupan sehari-hari menjadi representasi digital yang dapat dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis.
Pernahkah Anda bertanya ke mana perginya data pribadi Anda setelah mengakses aplikasi kesehatan, belanja online, atau sekadar check-in di mal, contohnya melalui aplikasi PeduliLindungi?
Pada puncak pandemi COVID-19, jutaan warga Indonesia secara rutin menggunakan PeduliLindungi untuk memindai QR code sebelum masuk tempat publik. Aplikasi ini mengumpulkan data lokasi, status vaksinasi, dan riwayat perjalanan, semuanya dilakukan demi tujuan kesehatan masyarakat. Namun, setelah pandemi mereda, publik mulai mempertanyakan: Siapa yang mengelola data tersebut? apakah datanya dihapus, disimpan, atau digunakan untuk tujuan lain? apakah kita pernah benar-benar memberikan persetujuan yang sadar dan sukarela?
Inilah contoh nyata dari datafikasi, yakni proses di mana aktivitas sehari-hari kita diubah menjadi data digital yang dapat dianalisis, digunakan, bahkan diperdagangkan. Di Indonesia, proses ini terjadi secara cepat namun sering tanpa kerangka etika yang kokoh atau partisipasi publik yang memadai.
Fenomena inilah yang menjadi fokus kajian Critical Data Studies (CDS) bidang kajian yang tidak hanya mempelajari data, tetapi juga mengkritisi siapa yang mengumpulkannya, untuk kepentingan apa, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Critical Data Studies (CDS) suatu bidang studi interdisipliner yang berkembang cepat di tengah kekhawatiran global akan penyalahgunaan data.
Data Bukan Netral: Kekuasaan dan Kepentingan di Balik Big Data
Dalam buku The Big Data Agenda (2018), Annika Richterich menyoroti bagaimana perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menentukan siapa yang boleh mengaksesnya, dan bagaimana data itu digunakan. Bahkan, penelitian ilmiah kini bergantung pada data yang dikendalikan korporasi, menciptakan hubungan saling ketergantungan yang rawan bias nilai dan konflik kepentingan.
CDS hadir sebagai respons terhadap dominasi pandangan teknokratis yang menganggap data sebagai sesuatu yang netral, objektif, dan bebas nilai. Padahal, data adalah konstruksi sosial hasil dari keputusan politik, ekonomi, dan teknologi. Dalam banyak narasi teknologi, data sering digambarkan sebagai sesuatu yang “netral”, “obyektif”, dan “fakta murni”. Namun, pendekatan Critical Data Studies (CDS) membantah klaim ini. Data bukan sekadar catatan pasif, melainkan hasil dari serangkaian proses, mulai dari siapa yang mengumpulkan, untuk apa, hingga bagaimana data itu diproses dan digunakan.
Menurut Annika Richterich dalam bukunya The Big Data Agenda, data selalu melibatkan relasi kuasa, terutama ketika perusahaan besar atau lembaga negara memonopoli akses dan kontrol atas data yang dihasilkan masyarakat. Bahkan dalam penelitian ilmiah, keterlibatan data komersial seperti dari media social bisa mengaburkan batas antara riset objektif dan kepentingan ekonomi.
Pada tahun 2022 sebagai contoh lain, pemerintah Indonesia melalui PT Pertamina meluncurkan kebijakan subsidi bahan bakar berbasis digital melalui aplikasi MyPertamina. Warga yang ingin membeli BBM subsidi diwajibkan mendaftarkan data pribadi dan kendaraannya. Dalam praktiknya Warga harus menyerahkan NIK, nomor polisi kendaraan, dan data teknis mobil/motor, aplikasi ini juga terhubung dengan sistem lain milik pemerintah (seperti Dukcapil dan Samsat).
Namun muncul pertanyaan kritis:
Apakah semua warga benar-benar memahami bagaimana data itu digunakan?
Siapa yang mengendalikan data tersebut apakah PT Pertamina, Kementerian ESDM, atau pihak ketiga (vendor teknologi)?
Apakah data ini bisa digunakan untuk profiling perilaku konsumsi energi atau bahkan ditransfer ke pihak swasta?
Dalam kajian Big Data Governance in Indonesia (Gunawan & Setiadi, 2023), disebutkan bahwa kurangnya transparansi dan perlindungan hukum membuat kebijakan digitalisasi publik rawan penyalahgunaan kekuasaan dan membuka celah komersialisasi data warga tanpa sepengetahuan mereka.
Dengan demikian, data tidak lagi berdiri sebagai “fakta netral”, melainkan bagian dari infrastruktur kekuasaan yang menentukan siapa yang mendapatkan layanan, siapa yang dikategorikan layak atau tidak, bahkan siapa yang mendapatkan atau kehilangan subsidi.
Persoalan Etika di Balik Riset Berbasis Big Data
Riset yang menggunakan Big Data, terutama di bidang kesehatan masyarakat, membawa implikasi etis yang serius. Di satu sisi, data digital dapat dimanfaatkan untuk melacak wabah, memprediksi tren penyakit, atau mengukur perilaku berisiko. Namun di sisi lain, banyak dari data tersebut berasal dari media sosial atau perangkat digital yang tidak pernah dimaksudkan untuk keperluan penelitian ilmiah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengguna sadar data mereka digunakan untuk riset? apakah ada persetujuan yang sah dan transparan? siapa yang bertanggung jawab bila terjadi penyalahgunaan?
Contohnya adalah studi analisis Twitter untuk mendeteksi pola stres atau gangguan mental, yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pengguna. Meskipun tujuannya untuk kebaikan publik, praktik ini menimbulkan perdebatan tentang batas antara kepentingan umum dan hak privasi individu. Big data juga telah merevolusi cara kita melakukan penelitian mulai dari analisis opini publik melalui media sosial hingga pemantauan persebaran penyakit menular. Namun di balik manfaat dan efisiensinya, muncul pertanyaan etis yang kompleks dan sering kali diabaikan.
1. Masalah Persetujuan yang Tidak Jelas (Informed Consent)
Dalam metode penelitian konvensional, subjek penelitian biasanya diminta menandatangani inform consent, yaitu persetujuan sadar dan sukarela setelah memahami tujuan, manfaat, dan risiko penelitian. Namun dalam era big data, hal ini menjadi semakin kabur. Contohnya, seorang peneliti bisa mengunduh ribuan cuitan publik dari Twitter atau konten Facebook dan menggunakannya untuk penelitian kesehatan mental, opini politik, atau perilaku sosial tanpa pernah menghubungi atau memberi tahu pemilik akun.
Di Indonesia, sebuah studi dari Universitas Indonesia (Sutanto & Andika, 2021) menemukan bahwa lebih dari 70 persen pengguna aplikasi kesehatan tidak memahami bagaimana data mereka digunakan oleh pengembang aplikasi maupun pihak ketiga. Ini menunjukkan kesenjangan besar antara praktik teknologi dan prinsip etika dasar dalam riset.
2. Privasi dan Pengawasan Terselubung
Ketika data digunakan untuk tujuan analisis, hal itu berpotensi mengungkap informasi pribadi seperti lokasi, kondisi kesehatan, atau hubungan sosial pengguna. Bahkan jika data tersebut telah dianonimkan, teknologi machine learning saat ini memungkinkan untuk mengaitkan kembali data ke individu tertentu melalui teknik re-identifikasi.
Contoh konkret muncul dari program smart city di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Pemerintah daerah bekerja sama dengan penyedia layanan digital untuk mengintegrasikan CCTV, data transportasi, dan layanan publik dalam satu dashboard berbasis AI. Walau bertujuan meningkatkan layanan, belum ada mekanisme transparan tentang: Siapa yang memiliki dan mengelola data? Berapa lama data disimpan? dan Apakah warga memiliki hak menolak atau meminta penghapusan datanya?
Tanpa payung hukum yang kuat, praktik ini berisiko berubah menjadi pengawasan massal yang mengancam kebebasan sipil.
3. Bias Algoritmik dan Diskriminasi Terselubung
Algoritma yang digunakan dalam pengolahan big data tidak netral. Ia dilatih dari data historis yang bisa mengandung bias rasial, gender, atau kelas sosial, dan dapat mereproduksi ketidakadilan tersebut secara sistematis. Misalnya, dalam riset kesehatan publik, jika data yang digunakan hanya berasal dari pengguna smartphone atau platform tertentu, maka hasil analisis akan bias terhadap kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses digital seperti masyarakat pedesaan atau kelompok marjinal.
Di Indonesia, penggunaan data BPJS Kesehatan sebagai basis untuk riset atau perencanaan kebijakan sering kali mengabaikan kelompok informal dan rentan yang belum terdaftar. Hal ini bisa menyebabkan kebijakan publik yang terlihat "berbasis data", tapi justru mengabaikan realitas sosial yang lebih luas.
4. Komersialisasi dan Konflik Kepentingan
Banyak riset big data, terutama yang menggunakan platform digital, secara tidak langsung bermitra atau bergantung pada perusahaan teknologi. Data yang digunakan peneliti sering berasal dari perusahaan seperti Google, Facebook, atau penyedia aplikasi lokal. Ini menimbulkan risiko konflik kepentingan: Apakah hasil riset akan dikendalikan oleh sponsor? Apakah publikasi hasil akan disensor? Apakah data akan digunakan kembali untuk tujuan bisnis?
Dalam konteks Indonesia, riset berbasis data dari aplikasi PeduliLindungi, MyPertamina, dan sistem transportasi digital telah menimbulkan kekhawatiran soal potensi pemanfaatan data riset oleh vendor swasta tanpa regulasi ketat atau akuntabilitas publik.
Konteks Indonesia: Tantangan Etika di Era Digitalisasi Layanan Publik
Di Indonesia, isu big data juga mulai menjadi perhatian, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan publik. Misalnya, integrasi data kependudukan oleh Dukcapil, BPJS, dan instansi lain berpotensi besar untuk efisiensi. Namun, minimnya kerangka etika yang jelas dan keterlibatan publik menimbulkan pertanyaan serius.
Salah satu kasus yang menimbulkan polemik adalah penggunaan data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Data lokasi, status vaksinasi, dan interaksi sosial pengguna dikumpulkan tanpa kejelasan soal keamanan penyimpanan data, siapa yang memiliki hak akses, dan apakah data tersebut akan dipakai untuk tujuan lain (seperti komersialisasi).
Dalam jurnal Big Data & Society, Paramadina dan Sibarani (2022) menegaskan bahwa “Indonesia masih belum memiliki sistem pengawasan independen terhadap penggunaan big data, sementara regulasi perlindungan data pribadi belum cukup kuat untuk menjamin hak warga”.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melaju pesat menuju digitalisasi layanan publik. Pemerintah mendorong transformasi digital di berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, energi, dan administrasi kependudukan. Dari sisi efisiensi, ini merupakan langkah positif. Namun dari sisi etika dan tata kelola data, Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang belum sepenuhnya terjawab.
1. Minimnya Regulasi Perlindungan Data yang Komprehensif
Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada 2022, implementasinya masih dalam tahap awal dan belum memiliki badan pengawas independen yang operasional. Hal ini membuat pengelolaan data oleh instansi pemerintah maupun swasta rentan disalahgunakan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Contohnya, pada 2021 terjadi kebocoran data 279 juta warga dari sistem BPJS Kesehatan yang dijual di forum hacker. Hingga kini, publik belum memperoleh kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana data itu bocor. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola data pada lembaga vital negara.
2. Aplikasi Wajib Negara: Efisiensi atau Pemaksaan?
Beberapa aplikasi pemerintah mewajibkan warga untuk menyerahkan data pribadi tanpa pilihan atau transparansi yang memadai. Dua contoh paling menonjol adalah:
PeduliLindungi: Di masa pandemi, aplikasi ini menjadi syarat akses ke ruang publik. Data yang dikumpulkan mencakup lokasi, riwayat perjalanan, status vaksinasi, bahkan hasil tes PCR. Namun, hingga 2023, belum ada audit publik terkait pemanfaatan dan penyimpanan data jutaan pengguna.
MyPertamina: Untuk membeli BBM subsidi, warga harus mendaftar lewat aplikasi ini dengan mencantumkan data kendaraan dan identitas pribadi. Proses ini bukan hanya memunculkan beban administratif, tetapi juga memunculkan kekhawatiran tentang siapa yang mengakses data dan untuk tujuan apa.
Dalam dua kasus ini, terlihat pola di mana negara menggunakan teknologi sebagai instrumen kontrol, namun tidak membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat terkait hak-hak digital mereka.
3. Integrasi Sistem Tanpa Pengawasan Publik
Program integrasi data nasional seperti Satu Data Indonesia bertujuan menyatukan berbagai data dari Dukcapil, BPJS, Kementerian Sosial, dan instansi lainnya. Tujuan utamanya adalah efisiensi layanan publik dan akurasi perencanaan kebijakan. Namun, menurut riset dari ELSAM (2023), proses integrasi ini: minim partisipasi publik, tidak transparan dalam pemilihan mitra teknologi dan vendor, dan belum memiliki mekanisme keberatan (grievance mechanism) bagi warga jika datanya digunakan tanpa persetujuan. Tanpa prinsip akuntabilitas dan partisipasi, digitalisasi yang ambisius justru berpotensi menciptakan arsitektur pengawasan sentralistik yang tidak demokratis.
4. Ketimpangan Akses dan Representasi Data
Digitalisasi sering kali dianggap sebagai solusi universal, padahal tidak semua warga memiliki akses dan literasi digital yang setara. Penggunaan big data oleh negara bisa menciptakan kebijakan publik yang bias terhadap kelompok digital-savvy dan mengabaikan kelompok marjinal seperti: masyarakat adat, komunitas miskin urban, lansia dan difabel yang tidak menggunakan perangkat digital. Hal ini menciptakan apa yang disebut "data exclusion" ketika kelompok-kelompok rentan justru tidak terlihat dalam sistem data, sehingga tidak diakomodasi dalam kebijakan.
Transformasi digital di Indonesia seharusnya tidak hanya menekankan kecepatan, integrasi, dan efisiensi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etika dan memperkuat hak warga atas datanya sendiri. Prinsip seperti: transparansi, persetujuan sadar (informed consent), keadilan digital, dan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) harus menjadi standar minimum dalam setiap program digital pemerintah. Tanpa itu semua, digitalisasi berisiko menjadi alat eksklusi dan pengawasan, alih-alih menjadi sarana pemberdayaan.
Membangun Etika Diskursus: Libatkan Publik, Jangan Sekadar Klaim ‘Untuk Kebaikan’
Annika Richterich dalam bukunya mengusulkan pendekatan etika diskursus (discourse ethics) yang dipengaruhi oleh pemikiran Jürgen Habermas. Prinsip utamanya: suatu kebijakan bisa dianggap etis jika dibentuk melalui dialog terbuka dengan semua pihak yang terdampak. Dalam konteks big data, ini berarti: warga negara harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan data, transparansi menjadi prinsip utama, tidak boleh ada monopoli pengetahuan oleh korporasi atau negara.
Alih-alih menganggap publik sebagai objek data, pendekatan ini menempatkan mereka sebagai subjek etis yang berhak bersuara.
Dalam berbagai kebijakan dan proyek digital pemerintah, frasa “demi kebaikan bersama” atau “untuk efisiensi layanan publik” kerap digunakan sebagai pembenaran pengumpulan dan penggunaan data berskala besar. Meski terdengar mulia, argumen tersebut sering menutupi fakta bahwa pengguna data (masyarakat) jarang diberi ruang untuk menyuarakan persetujuan atau keberatan.
Inilah kritik utama dari pendekatan etika diskursus (discourse ethics) yang diusung oleh filsuf Jürgen Habermas dan diadopsi oleh Annika Richterich dalam bukunya The Big Data Agenda. Menurut pendekatan ini, keputusan etis tidak bisa hanya ditentukan oleh pihak berkuasa atau ahli teknis, melainkan harus: dibahas secara terbuka, dipertimbangkan bersama oleh semua pihak yang terdampak, dan diambil melalui dialog yang setara.
Etika Diskursus menjadi penting dalam era big data karena:
Data menyangkut kehidupan manusia, bukan sekadar statistik: di balik setiap byte data, ada orang dengan hak, preferensi, dan kebutuhan. Oleh karena itu, penggunaan data harus menghormati martabat dan otonomi individu, bukan memperlakukannya sebagai objek pasif.
Klaim “kebaikan bersama” bisa bias dan eksklusif: Siapa yang mendefinisikan “kebaikan”? Pemerintah? Perusahaan teknologi? Tanpa melibatkan suara masyarakat, konsep ini bisa menjustifikasi pengawasan, diskriminasi, atau pengambilan keputusan yang tidak adil atas nama efisiensi.
Keadilan data hanya bisa dicapai melalui partisipasi: Dalam etika diskursus, keputusan yang sah secara moral adalah keputusan yang bisa diterima secara rasional oleh semua pihak yang terdampak. Ini menuntut keterbukaan terhadap keberatan, kritik, dan alternatif.
Bagaimana Etika Diskursus Dapat Diterapkan di Indonesia?
Kebijakan digital seperti MyPertamina, Satu Data Indonesia, hingga e-KTP harus memiliki dokumen publik yang menjelaskan terkait data apa yang dikumpulkan, siapa yang mengelola, untuk tujuan apa, dan bagaimana masyarakat dapat memberikan atau mencabut persetujuan. Masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas digital perlu dilibatkan dalam: perumusan kebijakan data, penilaian dampak etis (ethical impact assessment), dan pengawasan penggunaan data oleh pihak pemerintah atau swasta.
Sebuah contoh adalah pelibatan organisasi masyarakat sipil seperti ELSAM dalam konsultasi publik mengenai UU PDP. Praktik ini perlu diperluas secara sistematis di tingkat pusat dan daerah. Pengguna layanan public juga harus memiliki hak untuk mengetahui bagaimana datanya diproses, hak untuk memperbaiki kesalahan dalam data, dan hak untuk menolak pemrosesan data tertentu.
Etika diskursus mendorong pengakuan bahwa warga negara bukan sekadar objek pengawasan atau pelayanan, tetapi subjek moral dan politik yang berhak menentukan bagaimana data mereka digunakan karena digitalisasi bukanlah proyek netral. Di dalamnya terkandung nilai, asumsi, dan kepentingan, Oleh karena itu, tidak cukup hanya mempercepat integrasi dan efisiensi; kita perlu memperlambat sejenak untuk mendengar, mempertimbangkan, dan bernegosiasi secara etis.
Etika diskursus bukanlah hambatan bagi inovasi, melainkan jalan untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap menghargai prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi, dan keadilan sosial. Tanpa diskursus publik, klaim “untuk kebaikan bersama” bisa berubah menjadi “kebaikan bagi segelintir”.
Kesimpulan: Saatnya Bangun Kesadaran Kritis
Era big data membawa manfaat besar, tapi juga menyimpan risiko besar jika tidak dikawal secara etis dan demokratis. Kajian kritis terhadap praktik big data bukanlah bentuk penolakan teknologi, melainkan cara untuk memastikan bahwa perkembangan digital tetap selaras dengan keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. Di Indonesia, dengan cepatnya laju digitalisasi, pendekatan Critical Data Studies perlu mulai diarusutamakan baik dalam riset akademik, kebijakan publik, maupun literasi digital masyarakat.
Kita hidup di zaman ketika hampir setiap aspek kehidupan terekam sebagai data dari transaksi sehari-hari hingga catatan kesehatan dan preferensi pribadi. Pemerintah, swasta, bahkan institusi akademik berlomba memanfaatkan data demi efisiensi, inovasi, dan kemajuan. Namun, di balik semangat digitalisasi itu, terdapat jurang etika dan keadilan yang harus kita hadapi secara sadar dan kritis.
Melalui pendekatan Critical Data Studies, kita diajak memahami bahwa data bukan sekadar angka netral, tetapi hasil dari proses sosial, ekonomi, dan politik yang penuh bias dan kepentingan. Etika dalam penggunaan big data bukanlah pelengkap, melainkan syarat utama bagi keberlanjutan sistem digital yang adil dan demokratis.
Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan: antara mengejar efisiensi digital semata, atau membangun sistem data yang berbasis partisipasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak individu. Undang-undang dan teknologi saja tidak cukup; kita butuh diskursus publik yang melibatkan warga sebagai subjek, bukan objek dari kebijakan data.
Digitalisasi yang baik harus disertai dengan demokratisasi data di mana masyarakat memiliki kontrol, pilihan, dan suara atas bagaimana data mereka digunakan. Hanya dengan begitu, transformasi digital tidak hanya akan canggih secara teknis, tapi juga beradab secara moral dan adil secara sosial. (*)
Oleh:
Adhitya Putra
(Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)
| Nota Keuangan RAPBN 2026, Said Abdullah : Realistis! |

|
|---|
| Said Abdullah : Puncak Bulan Bung Karno 2025 di Pusara Beliau di Kota Blitar |

|
|---|
| Ketua Banggar DPR : Indonesia Perlu Desak PBB Sanksi Israel |

|
|---|
| Kenegarawanan Megawati dan Prabowo di Peringatan Hari Pancasila |

|
|---|
| Tantangan Pemerintah Antisipasi shortfall Pajak Imbas Rendahnya Harga Komoditas Ekspor |

|
|---|
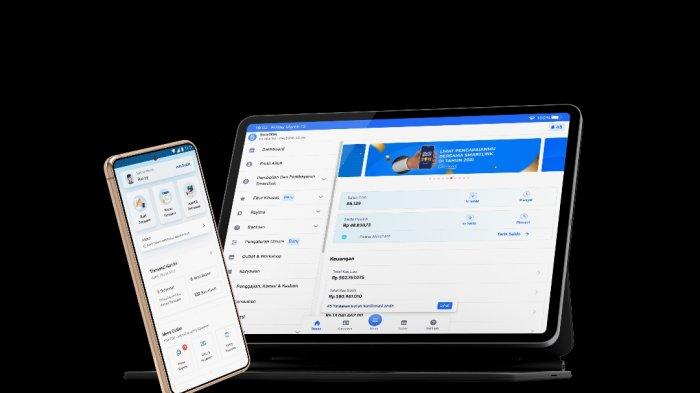
















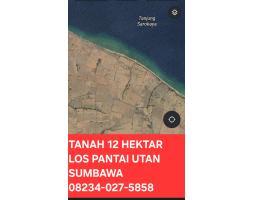



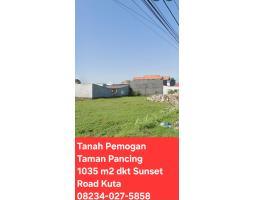















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.