Opini
Big Data dan Etika: Mengapa Kita Harus Kritis dalam Era Datafikasi
Pernahkah Anda bertanya ke mana perginya data pribadi Anda setelah mengakses aplikasi kesehatan?
Dalam metode penelitian konvensional, subjek penelitian biasanya diminta menandatangani inform consent, yaitu persetujuan sadar dan sukarela setelah memahami tujuan, manfaat, dan risiko penelitian. Namun dalam era big data, hal ini menjadi semakin kabur. Contohnya, seorang peneliti bisa mengunduh ribuan cuitan publik dari Twitter atau konten Facebook dan menggunakannya untuk penelitian kesehatan mental, opini politik, atau perilaku sosial tanpa pernah menghubungi atau memberi tahu pemilik akun.
Di Indonesia, sebuah studi dari Universitas Indonesia (Sutanto & Andika, 2021) menemukan bahwa lebih dari 70 persen pengguna aplikasi kesehatan tidak memahami bagaimana data mereka digunakan oleh pengembang aplikasi maupun pihak ketiga. Ini menunjukkan kesenjangan besar antara praktik teknologi dan prinsip etika dasar dalam riset.
2. Privasi dan Pengawasan Terselubung
Ketika data digunakan untuk tujuan analisis, hal itu berpotensi mengungkap informasi pribadi seperti lokasi, kondisi kesehatan, atau hubungan sosial pengguna. Bahkan jika data tersebut telah dianonimkan, teknologi machine learning saat ini memungkinkan untuk mengaitkan kembali data ke individu tertentu melalui teknik re-identifikasi.
Contoh konkret muncul dari program smart city di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Pemerintah daerah bekerja sama dengan penyedia layanan digital untuk mengintegrasikan CCTV, data transportasi, dan layanan publik dalam satu dashboard berbasis AI. Walau bertujuan meningkatkan layanan, belum ada mekanisme transparan tentang: Siapa yang memiliki dan mengelola data? Berapa lama data disimpan? dan Apakah warga memiliki hak menolak atau meminta penghapusan datanya?
Tanpa payung hukum yang kuat, praktik ini berisiko berubah menjadi pengawasan massal yang mengancam kebebasan sipil.
3. Bias Algoritmik dan Diskriminasi Terselubung
Algoritma yang digunakan dalam pengolahan big data tidak netral. Ia dilatih dari data historis yang bisa mengandung bias rasial, gender, atau kelas sosial, dan dapat mereproduksi ketidakadilan tersebut secara sistematis. Misalnya, dalam riset kesehatan publik, jika data yang digunakan hanya berasal dari pengguna smartphone atau platform tertentu, maka hasil analisis akan bias terhadap kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses digital seperti masyarakat pedesaan atau kelompok marjinal.
Di Indonesia, penggunaan data BPJS Kesehatan sebagai basis untuk riset atau perencanaan kebijakan sering kali mengabaikan kelompok informal dan rentan yang belum terdaftar. Hal ini bisa menyebabkan kebijakan publik yang terlihat "berbasis data", tapi justru mengabaikan realitas sosial yang lebih luas.
4. Komersialisasi dan Konflik Kepentingan
Banyak riset big data, terutama yang menggunakan platform digital, secara tidak langsung bermitra atau bergantung pada perusahaan teknologi. Data yang digunakan peneliti sering berasal dari perusahaan seperti Google, Facebook, atau penyedia aplikasi lokal. Ini menimbulkan risiko konflik kepentingan: Apakah hasil riset akan dikendalikan oleh sponsor? Apakah publikasi hasil akan disensor? Apakah data akan digunakan kembali untuk tujuan bisnis?
Dalam konteks Indonesia, riset berbasis data dari aplikasi PeduliLindungi, MyPertamina, dan sistem transportasi digital telah menimbulkan kekhawatiran soal potensi pemanfaatan data riset oleh vendor swasta tanpa regulasi ketat atau akuntabilitas publik.
Konteks Indonesia: Tantangan Etika di Era Digitalisasi Layanan Publik
Di Indonesia, isu big data juga mulai menjadi perhatian, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan publik. Misalnya, integrasi data kependudukan oleh Dukcapil, BPJS, dan instansi lain berpotensi besar untuk efisiensi. Namun, minimnya kerangka etika yang jelas dan keterlibatan publik menimbulkan pertanyaan serius.
Salah satu kasus yang menimbulkan polemik adalah penggunaan data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Data lokasi, status vaksinasi, dan interaksi sosial pengguna dikumpulkan tanpa kejelasan soal keamanan penyimpanan data, siapa yang memiliki hak akses, dan apakah data tersebut akan dipakai untuk tujuan lain (seperti komersialisasi).
Dalam jurnal Big Data & Society, Paramadina dan Sibarani (2022) menegaskan bahwa “Indonesia masih belum memiliki sistem pengawasan independen terhadap penggunaan big data, sementara regulasi perlindungan data pribadi belum cukup kuat untuk menjamin hak warga”.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melaju pesat menuju digitalisasi layanan publik. Pemerintah mendorong transformasi digital di berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, energi, dan administrasi kependudukan. Dari sisi efisiensi, ini merupakan langkah positif. Namun dari sisi etika dan tata kelola data, Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang belum sepenuhnya terjawab.
| Nota Keuangan RAPBN 2026, Said Abdullah : Realistis! |

|
|---|
| Said Abdullah : Puncak Bulan Bung Karno 2025 di Pusara Beliau di Kota Blitar |

|
|---|
| Ketua Banggar DPR : Indonesia Perlu Desak PBB Sanksi Israel |

|
|---|
| Kenegarawanan Megawati dan Prabowo di Peringatan Hari Pancasila |

|
|---|
| Tantangan Pemerintah Antisipasi shortfall Pajak Imbas Rendahnya Harga Komoditas Ekspor |

|
|---|
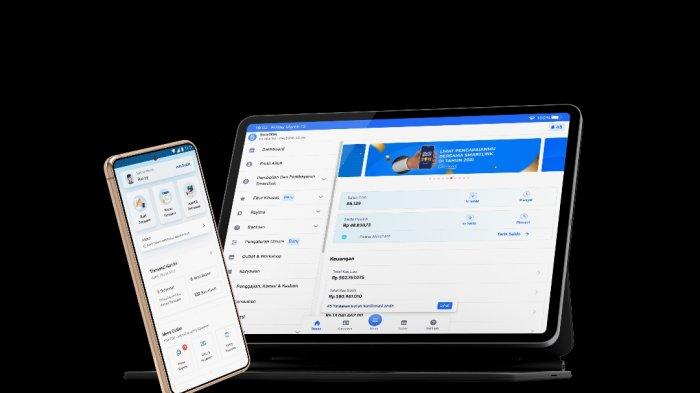














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.