Opini
Big Data dan Etika: Mengapa Kita Harus Kritis dalam Era Datafikasi
Pernahkah Anda bertanya ke mana perginya data pribadi Anda setelah mengakses aplikasi kesehatan?
1. Minimnya Regulasi Perlindungan Data yang Komprehensif
Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada 2022, implementasinya masih dalam tahap awal dan belum memiliki badan pengawas independen yang operasional. Hal ini membuat pengelolaan data oleh instansi pemerintah maupun swasta rentan disalahgunakan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Contohnya, pada 2021 terjadi kebocoran data 279 juta warga dari sistem BPJS Kesehatan yang dijual di forum hacker. Hingga kini, publik belum memperoleh kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana data itu bocor. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola data pada lembaga vital negara.
2. Aplikasi Wajib Negara: Efisiensi atau Pemaksaan?
Beberapa aplikasi pemerintah mewajibkan warga untuk menyerahkan data pribadi tanpa pilihan atau transparansi yang memadai. Dua contoh paling menonjol adalah:
PeduliLindungi: Di masa pandemi, aplikasi ini menjadi syarat akses ke ruang publik. Data yang dikumpulkan mencakup lokasi, riwayat perjalanan, status vaksinasi, bahkan hasil tes PCR. Namun, hingga 2023, belum ada audit publik terkait pemanfaatan dan penyimpanan data jutaan pengguna.
MyPertamina: Untuk membeli BBM subsidi, warga harus mendaftar lewat aplikasi ini dengan mencantumkan data kendaraan dan identitas pribadi. Proses ini bukan hanya memunculkan beban administratif, tetapi juga memunculkan kekhawatiran tentang siapa yang mengakses data dan untuk tujuan apa.
Dalam dua kasus ini, terlihat pola di mana negara menggunakan teknologi sebagai instrumen kontrol, namun tidak membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat terkait hak-hak digital mereka.
3. Integrasi Sistem Tanpa Pengawasan Publik
Program integrasi data nasional seperti Satu Data Indonesia bertujuan menyatukan berbagai data dari Dukcapil, BPJS, Kementerian Sosial, dan instansi lainnya. Tujuan utamanya adalah efisiensi layanan publik dan akurasi perencanaan kebijakan. Namun, menurut riset dari ELSAM (2023), proses integrasi ini: minim partisipasi publik, tidak transparan dalam pemilihan mitra teknologi dan vendor, dan belum memiliki mekanisme keberatan (grievance mechanism) bagi warga jika datanya digunakan tanpa persetujuan. Tanpa prinsip akuntabilitas dan partisipasi, digitalisasi yang ambisius justru berpotensi menciptakan arsitektur pengawasan sentralistik yang tidak demokratis.
4. Ketimpangan Akses dan Representasi Data
Digitalisasi sering kali dianggap sebagai solusi universal, padahal tidak semua warga memiliki akses dan literasi digital yang setara. Penggunaan big data oleh negara bisa menciptakan kebijakan publik yang bias terhadap kelompok digital-savvy dan mengabaikan kelompok marjinal seperti: masyarakat adat, komunitas miskin urban, lansia dan difabel yang tidak menggunakan perangkat digital. Hal ini menciptakan apa yang disebut "data exclusion" ketika kelompok-kelompok rentan justru tidak terlihat dalam sistem data, sehingga tidak diakomodasi dalam kebijakan.
Transformasi digital di Indonesia seharusnya tidak hanya menekankan kecepatan, integrasi, dan efisiensi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etika dan memperkuat hak warga atas datanya sendiri. Prinsip seperti: transparansi, persetujuan sadar (informed consent), keadilan digital, dan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) harus menjadi standar minimum dalam setiap program digital pemerintah. Tanpa itu semua, digitalisasi berisiko menjadi alat eksklusi dan pengawasan, alih-alih menjadi sarana pemberdayaan.
Membangun Etika Diskursus: Libatkan Publik, Jangan Sekadar Klaim ‘Untuk Kebaikan’
Annika Richterich dalam bukunya mengusulkan pendekatan etika diskursus (discourse ethics) yang dipengaruhi oleh pemikiran Jürgen Habermas. Prinsip utamanya: suatu kebijakan bisa dianggap etis jika dibentuk melalui dialog terbuka dengan semua pihak yang terdampak. Dalam konteks big data, ini berarti: warga negara harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan data, transparansi menjadi prinsip utama, tidak boleh ada monopoli pengetahuan oleh korporasi atau negara.
Alih-alih menganggap publik sebagai objek data, pendekatan ini menempatkan mereka sebagai subjek etis yang berhak bersuara.
Dalam berbagai kebijakan dan proyek digital pemerintah, frasa “demi kebaikan bersama” atau “untuk efisiensi layanan publik” kerap digunakan sebagai pembenaran pengumpulan dan penggunaan data berskala besar. Meski terdengar mulia, argumen tersebut sering menutupi fakta bahwa pengguna data (masyarakat) jarang diberi ruang untuk menyuarakan persetujuan atau keberatan.
Inilah kritik utama dari pendekatan etika diskursus (discourse ethics) yang diusung oleh filsuf Jürgen Habermas dan diadopsi oleh Annika Richterich dalam bukunya The Big Data Agenda. Menurut pendekatan ini, keputusan etis tidak bisa hanya ditentukan oleh pihak berkuasa atau ahli teknis, melainkan harus: dibahas secara terbuka, dipertimbangkan bersama oleh semua pihak yang terdampak, dan diambil melalui dialog yang setara.
Etika Diskursus menjadi penting dalam era big data karena:
| Nota Keuangan RAPBN 2026, Said Abdullah : Realistis! |

|
|---|
| Said Abdullah : Puncak Bulan Bung Karno 2025 di Pusara Beliau di Kota Blitar |

|
|---|
| Ketua Banggar DPR : Indonesia Perlu Desak PBB Sanksi Israel |

|
|---|
| Kenegarawanan Megawati dan Prabowo di Peringatan Hari Pancasila |

|
|---|
| Tantangan Pemerintah Antisipasi shortfall Pajak Imbas Rendahnya Harga Komoditas Ekspor |

|
|---|
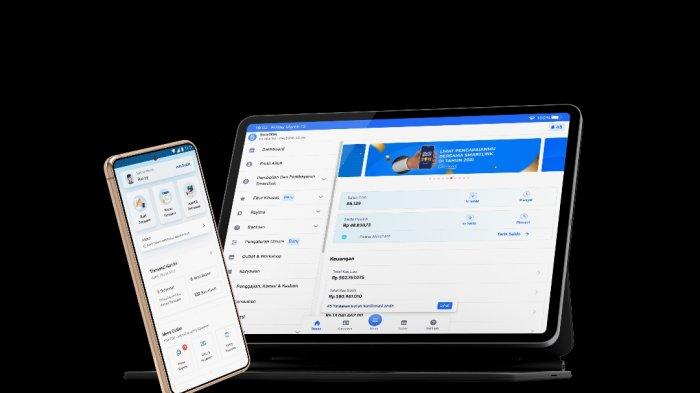








![[FULL] Detik-detik Pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam HUT ke-80 RI di Istana Negara Merdeka](https://img.youtube.com/vi/CEJ63zeH3cM/mqdefault.jpg)






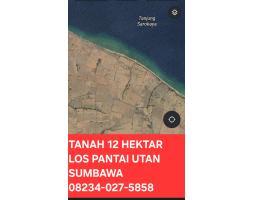



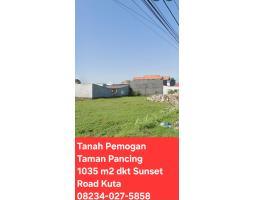















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.